BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut teori psikologi, anak yang rasional selalu bertindak sesuai tingkatan perkembangan umur mereka. Ia mengadakan reaksi-reaksi terhadap lingkungannya, atau adanya aksi dari lingkungan maka ia melakukan kegiatan atau aktivitas. Dalam pendidikan kuno aktivitas anak tidak pernah diperhatikan karena menurut pandangan mereka anak dilahirkan tidak lain sebagai “orang dewasa dalam bentuk kecil”. Ia harus diajarkan menurut kehendak orang dewasa. Karena itu ia harus menerima dan mendengar apa-apa yang diberikan dan disampaikan orang dewasa/guru tanpa dikritik. Anak tak obahnya seperti gelas kosong yang pasif menerima apa saja yang dituangkan ke dalamnya.
Pandangan yang lebih maju (modern) menganggap hal tersebut di atas sesuatu yang keterlaluan, menyiksa serta mengingkari harkat kemanusiaan anak. Aliran modern ini merombak dan mengubah pandangan itu dan mengantikannya dengan penekanan pada kegiatan anak dalam proses pembelajaran. Anak aktif mencari sendiri dan bekerja sendiri. dengan demikian anak akan lebih bertanggung jawab dan beani mengambil keputusan sehingga pengertain mengenai suatu persoalan benar-benar mereka pahami dengan baik. Walaupun mereka mengambil keputusan sendiri berdasarkan pertingan kata hatinya, namun putusan mereka tersebut berhubungan juga dengan masyarakat, sebab individu itu baru berarti kalau ia telah berada dalam masyarakat.
Di dalam proses belajar-mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar.
Teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instrukstur. Pengertian lain ialah sebagai teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik. Di dalam kenyataan cara atau metode mengajar atau teknik penyajian yang digunakan guru untuk menyampaikan informasi atau massage lisan kepada siswa berbeda dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan serta sikap. Metode yang digunakan untuk memotivasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi ataupun untuk menjawab suatu pertanyaan akan berbeda dengan metode yang diguanakan untuk tujuan agar siswa mampu berpikir dan mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam menghadapi segala persoalan.
Kita mengenal bermacam-macam teknik penyajian dari yang tradisional, yang digunakan sejak dahulu kala, tetapi juga yang modern, yang digunakan baru akhir-akhir ini saja.
Perkembangan selanjutnya para ahli masih tersu mengadakan penelitian dan eksperimen agar dapat menemukan teknik penyajian yang dipandang paling efektif untuk pelajaran tertentu. apakah hal itu akan terjawab, kita serahkan pada hasil penelitian para ahli tersebut.
Dari bermacam-macam teknik mengajar itu, ada yang menekankan peranan guru yang utama dalam pelaksanaan penyajian, tetapi ada pula yang menekankan pada media hasil teknologi meoderen seperti televise, radio, kasset, video-tape, film, head-projector, mesin-belajar dan lain-lain, bahkan telah menggukanan bantuan satelit. Ada pula teknik penyajian yang hanya digunakan untuk sejumlah siswa yang terbatas, tetapi ada pula yang digunakan untuk sejumlah siswa yang tidak terbatas.
Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah asal pakai, tetapi setelah melalui seleksi yang berkesesuaian dengan perumuan tujuan intruksional khusus. Sebab dalam kegiaatan belajar mengajar, mengajar bukan semata persoalan menceritakan. Belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari perenungan informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang langgeng. Yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar aktif.
Agar belajar menjadi aktif siswa harus mengerjakan banyak sekali tugas. Mereka harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif harus gesit, menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan tempat duduk mereka, bergerak leluasa dan berfikir keras (moving about dan thinking aloud)
Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik, kita perlu mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan tentangnya, dan membahasnya dengan orang lain. Bukan Cuma itu, siswa perlu “mengerjakannya”, yakni menggambarkan sesuatu dengan cara mereka sendiri, menunjukkan contohnya, mencoba mempraktekkan keterampilan, dan mengerjakan tugas yang menuntut pengetahuan yang telah atau harus mereka dapatkan.
Dengan menyadari gejala-gejala atau kenyataan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis penulis mengambil judul “Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Dengan Menerapkan Model Pengajaran Tuntas Pada Siswa Kelas IV SDN ABC Kec. Kota Jakarta Tahun Pelajaran 2009/2010.”
B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahnnya sebagi berikut:
1. Apakah penerapan model pembelajaran tuntas dapat meningkatkan prestasi siswa terhadap materi pelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa Kelas IV SDN ABC Kec. Kota Jakarta?
2. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran tuntas dalam meningkatkan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa Kelas IV SDN ABC Kec. Kota Jakarta?
C. Pemecahan Masalah
Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam, khususnya di SDN ABC Kec. Kota Jakarta, salah satunya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran tuntas. Dengan menerapkan model pembelajaran ini diharapkan prestasi serta motivasi belajar Pendidikan Agama Islam dapat meningkat.
D. Batasan Masalah
1. Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa Kelas IV SDN ABC Kec. Kota Jakarta tahun pelajaran 2009/2010.
2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April semester genap tahun palajaran 2009/2010.
3. Materi yang disampaikan adalah pokok bahasan kisah-kisah Nabi.
E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Ingin mengetahui bagaimanakah peningkatan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam setelah diterapkannya model pembelajaran tuntas pada siswa Kelas IV SDN ABC Kec. Kota Jakarta.
2. Ingin mengetahui pengaruh model pembelajaran tuntas dalam meningkatkan prestasi dan motivasi belajar terhadap materi pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah diterapkan model pembelajaran tuntas pada siswa Kelas IV SDN ABC Kec. Kota Jakarta.
F. Manfaat Penelitian
Adapun maksud penulis mengadakan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:
1. Memberikan informasi tentang model pembelajaran yang sesuai dengan proses belajar-mengajar Pendidikan Agama Islam.
2. Meningkatkan pestasi prestasi dan motivasi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam
3. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman siswa belajar Pendidikan Agama Islam
4. Sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
5. Menerapkan metode yang tepat sesuai dengan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam.
G. Definisi Operasional Variabel
Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka perlu didefinisikan hal-hal sebagai berikut:
1. Model Pengajaran Tuntas adalah:
Merupakan model pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam kelas, dengan asumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua peserta didik akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh bahan yang dipelajari (Ramayulis, 193:2005).
2. Motivasi belajar adalah:
Suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
2. Prestasi belajar adalah:
Hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau dalam bentuk skor, setelah siswa mengikuti pelajaran.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar
1. Pengertian Belajar
Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan dalam kepustakaan. Yang dimaksud belajar yaitu perbuatan murid dalam bidang material, formal serta fungsional pada umumnya dan bidang intelektual pada khususnya. Jadi belajar merupakan hal yang pokok. Belajar merupakan suatu perubahan pada sikap dan tingkah laku yang lebih baik, tetapi kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk.
Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan harus merupakan akhir dari pada periode yang cukup panjang. Berapa lama waktu itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti, tetapi perubahan itu hendaklah merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Belajar merupakan suatu proses yang tideak dapat dilihat dengan nyata proses itu terjadi dalam diri seserorang yang sedang mengalami belajar. Jadi yang dimaksud dengan belajar bukan tingkah laku yang nampak, tetapi prosesnya terjadi secara internal di dalam diri individu dalam mengusahakan memperoleh hubungan-hubungan baru.
2. Pengertian Prestasi Belajar
Sebelum dijelaskan pengertian mengenai prestasi belajar, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang pengertian prestasi. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai. Dengan demikian bahwa prestasi merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah melakukan sesuatu pekerjaan/aktivitas tertentu.
Jadi prestasi adalah hasil yang telah dicapai oleh karena itu semua individu dengan adanya belajar hasilnya dapat dicapai. Setiap individu belajar menginginkan hasil yang yang sebaik mungkin. Oleh karena itu setiap individu harus belajar dengan sebaik-baiknya supaya prestasinya berhasil dengan baik. Sedang pengertian prestasi juga ada yang mengatakan prestasi adalah kemampuan. Kemampuan di sini berarti yan dimampui individu dalam mengerjakan sesuatu.
3. Pedoman Cara Belajar
Untuk memperoleh prestasi/hasil belajar yang baik harus dilakukan dengan baik dan pedoman cara yang tapat. Setiap orang mempunyai cara atau pedoman sendiri-sendiri dalam belajar. Pedoman/cara yang satu cocok digunakan oleh seorang siswa, tetapi mungkin kurang sesuai untuk anak/siswa yang lain. Hal ini disebabkan karena mempunyai perbedaan individu dalam hal kemampuan, kecepatan dan kepekaan dalam menerima materi pelajaran.
Oleh karena itu tidaklah ada suatu petunjuk yang pasti yang harus dikerjakan oleh seorang siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Tetapi faktor yang paling menentukan keberhasilan belajar adalah para siswa itu sendiri. Untuk dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya harus mempunyai kebiasaan belajar yang baik.
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belajar
Adapun faktor-faktor itu, dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu:
a. Faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang kita sebut faktor individu.
Yang termasuk ke dalam faktor individu antara lain faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi.
b. Faktor yang ada pada luar individu yang kita sebut dengan faktor sosial
Sedangkan yang faktor sosial antara lain faktor keluarga, keadaan rumah tangga, guru, dan cara dalam mengajarnya, lingkungan dan kesempatan yang ada atau tersedia dan motivasi sosial.
Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar di atas menunjukkan bahwa belajar itu merupaka proses yang cukup kompleks. Artinya pelaksanaan dan hasilnya sangat ditentukan oleh faktor-faktor di atas. Bagi siswa yang berada dalam faktor yang mendukung kegiatan belajar akan dapat dilalui dengan lancar dan pada gilirannya akan memperoleh prestasi atau hasil belajar yang baik.
Sebaliknya bagi siswa yang berada dalam kondisi belajar yang tidak menguntungkan, dalam arti tidak ditunjang atau didukung oleh faktor-faktor diatas, maka kegiatan atau proses belajarnya akan terhambat atau menemui kesulitan.
C. Movitasi Belajar
1. Pengertian Motivasi
Istilah motivasi menunjuk kepada semua gejala yang tekandung dalam stimulasi tindakaan ke arah tujuan tertentu di mana sebelumnya tidak ada gerakan menuju ke arah tujuan tersebut. Motivasi dapat berupa dorongan-dorongan dasar atau internal dan insentif di luar diri individu atau hadiah. Sebagai suatu masalah di dalam kelas, motivasi adalah proses membangkitkan, mempertahankan, dan mengontrol minat-minat.
Suatu prinsip yang mendasari tingkah laku ialah bahwa individu selalu mengambil jalan terpendek menuju suatu tujuan. Orang dewasa mungkin berpandangan bahwa di dalam kelas para siswa harus mengabdikan dirinya kepada penguasaan kurikulum. Akan tetapi, para siswa tidak selalu melihat tugas-tugas sekolah sebagai jalan terbaik yang menuju kearah kebebasan, produktivitas, kedewasaan, atau apa saja yang dipandang mereka sebagai perkembangan yang disukai. Dalam hubungan ini tugas guru adalah menolong mereka untuk memilih topik, kegiatan, atau tujuan yang bermanfaat, baik untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek.
D. Prinsip Motivasi
Prinsip ini disusun atas dasar penelitian yang seksama dalam rangka mendorong motivasi belajar para siswa di sekolah berdsarkan pandangan demokratis. Ada 17 prinsip motivasi yang dapat dilaksanakan:
1. Pujian lebih efektif daripada hukuman. Hukuman bersifat menghentikan suatu perbuatan, sedangkan pujian bersifat menghargai apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pujian lebih besar nilainya bagi motivasi belajar.
2. Semua siswa mempunyai kebutuhan psikologis (yang bersifat dasar) yang harus mendapat pemuasan. Kebutuhan-kebutuhan itu menyatakan diri dalam berbagai bentuk yang berbeda. Para siswa yang dapat memenuhi kebutuhannya secara efektif melalui kegiatan-kegiatan belajar hanya memerlukan sedikit bantuan dalam motivasi dan disiplin.
3. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Kepuasan yang didapat oleh individu itu sesuai dengan ukuran yang ada di dalam dirinya sendiri.
4. Jawaban (perbuatan) yang serasi (sesuai dengan keinginan) memerluakn usaha penguatan (reinformancement). Apabila suatu perbuatan belajar mencapai tujuan, maka perbuatan itu perlu segera diulang kembali beberapa menit kemudian sehingga hasilnya lebih mantap. Penguatan ini perlu dilakukan dalam setiap tingkatan pengalaman belajar.
5. Motivasi mudah menjalar luas terhadap orang lain. Guru yang berminat tinggi dan antusias akan mempengaruhi para siswa sehigga mereka juga berminat tinggi dan antusias. Siswa yang antusias akan mendorong motivasi para siswa lainnya.
6. Pemahaman yang jelas tentang tujuan belajar akan merangsang motivasi. Apabila seseorang telah menyadari tujuan yang hendak dicapainya, perbuatannya kearah itu akan lebih besar daya dorongnya.
7. Tugas-tugas yang besumber dari diri sendiri akan menimbulkan minat yang lebih besar untuk mengerjakannya ketimbang bila tugas-tugas itu dipaksakan oleh guru. Apabila siswa diberi kesempatan untuk menemukan masalah sendiri dan memecahkannya sendiri, ia akan mengembangkan motivasi ddan disiplin yang lebih baik.
8. Pujian-pujian yang datangnya dari luar (external rewards) kadang-kadang diperlukan dan cukup efektif untuk merangsang minat yang sebenarnya. Berkat dorongan orang lain, misalnya untuk memperoleh angka yang tinggi, siswa akan berusaha lebih giat karena minatnya menjadi lebih besar.
9. Teknik dan prosedur mengajar yang bermacam-macam itu efektif untuk memelihara minat siswa. Cara mengajar yang bervariasi ini akan meimbulkan situasi belajar yang menantang dan menyenangkan.
10. Minat khusus yang dimiliki oleh siswa berdaya guna untuk mempelajari hal-hal lainnya. Minat khusus yang telah dimiliki oleh siswa, misalnya minat bermain bola basket, akan mudah ditransferkan kepada minat dalam bidang studi atau dihubungkan dengan masalah tertentu dalam bidang studi.
11. Kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang minat para siswa yang tergolong kurang tidak ada artinya bagi para siswa yang tergolong pandai. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat abilitas pada siswa tersebut. Oleh karena itu, guru yang hendak membangkitkan minat para siswanya hendaknya menyesuaikan usahanya dengan kondisi yang ada pada mereka.
12. Tekanan dari kelompok siswa umumnya lebih efketif dalam memotivasi dibandingkan dengan tekanan atau paksaan dari orang dewasa.
13. Motivasi erat hubungannya dengan kreativitas siswa. Dengan teknik mengajar tertentu, motivasi siswa dapat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan kreatif. Motivasi yang telah dimiliki oleh siswa, apabila diberi semacam hambatan, misalnya adanya ujian yang mendadak, peraturan sekolah, kreativitasnya akan meningkat sehinga dia lolos dari hambatan itu.
14. Kecemasan akan meimbulkan kesulitan belajar. Kecemasan ini akan mengganggu perbuatan belajar sebab akan mengakibatkan pindahnya perhatiannya kepada hal lain sehingga kegiatan belajarnya menjadi tidak efketif.
15. Kecemasan dan frustasi dapat membantu siswa berbuat lebih baik. Emosi yang lemah dapat menimbulkan perbuatan yang lebih energetik, kelakuan yang lebih bergairah.
16. Tugas yang terlalu sukar dapat mengakibatkan frustasi sehingga dapat menuju kepada demoralisasi. Karena terlalu sulitnya tugas itu, para siswa cenderung melakukan hal-hal yang tidak wajar sebagai manifestasi dari frustasi yang terkandung didalam dirinya.
17. Tiap siswa mempunyai tingkat frustasi dan toleransi yang berlain-lainan. Ada siswa yang kegagalannya justru menimbulkan insentif, tetapi ada anak yang selalu berhasil malahan menjadi cemas terhadap kemungkinan timbulnya kegagalan. Hal ini bergantung pada stabilitas emosi masing-masing.
E. Teknik Memotivasi Berdasarkan Teori Kebutuhan
1. Pemberian Penghargaan atau Ganjaran
Teknik ini dianggap berhasil bila menumbuhkembangkan minat anak untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu. Tujuan pemberian penghargaan adalah membangkitkan atau mengembangkan minat. Jadi, penghargaan berperan untuk membuat pendahuluan saja. Penghargaan adalah alat, bukan tujuan. Hendaknya diperhatikan jangan sampai penghargaan ini menjadi tujuan. Tujuan pemberian penghargaan karena telah melakukan kegiatan belajar dengan baik, ia akan terus melakukan kegiatan belajarnya sendiri di luar kelas.
2. Pemberian Angka atau Grade
Apabila pemberian angka atau grade didasarkan atas perbandingan interpersonal dalam prestasi akademis, hal ini akan menimbulkan dua hal: anak yang mendapat angka baik dan anak yang mendapat angka jelek. Pada anak yang mendapat angkan jelek mungkin akan berkembang rasa rendah diri dan tak ada semangat terhadap pekerjaan-pekerjaan sekolah.
Dalam hubungan ini, William Glasser dalam Schools without Failure (1969) (dalam Hamalik, Umar, 2000:184) menyatakan, “Karena grade atau angka itu lebih banyak menekankan kegagalan daripada keberhasilan, dan karena kegagalan itu merupakan dasar bagi timbulnya masalah-masalah, maka saya menyarankan sistem pelaporan kemajuan siswa yang keseluruhannya menghilangkan kegagalan. Saya menyarankan jangan ada siswa yang tergolong gagal atau hal-hal yang menyebabkan ia merasa gagal dengan adanya sistem angka.”
3. Keberhasilan dan Tingkat Aspirasi
Istilah “tingkat aspirasi” menunjuk kepada tingkat pekerjaan yang diharapkan pada masa depan berdasarkan keberhasilan atau kegagalan dalam tugas-tugas yang mendahuluinya. Konsep ini berkaitan erat dengan konsep seseorang tentang dirinya dan kekuatan-kekuatannya.
Menurut Smith, apa yang dicita-citakan seseorang untuk dikerjakan pada masa datang tergantung pada pengamatannya tentang apa-apa yang mungkin baginya. Menurut Borow, tingkat aspirasi banyak bergantung pada inteligensi, status sosial ekonomi, hubungan, dan harapan orang tua. Akan tetapi, faktor yang paling kuat adalah perbandingan besar-kecilnya (proporsi) pengalaman tentang keberhasilan dan kegagalan (Hamalik, Oemar, 2000:185).
Dalam hubungan ini guru dapat menggunakan prinsip bahwa tujuan-tujuan harus dapat dicapai dan para siswa merasa bahwa mereka akan mampu mencapainya.
4. Pemberian pujian
Teknik lain untuk memberikan motivasi adalah pujian. Namun, harus diingat bahwa efek pujian itu bergantung pada siapa yang memberi pujian dan siapa yang menerima pujian itu. Para siswa yang sangat membutuhkan keselamatan dan harga diri, mengalami kecemasan, dan merasa bergantung pada orang lain akan rsponsif terhadap pujian. Pujian dapat ditunjukkan baik secara verbal maupun secara nonverbal. Dalam bentuk nonverbal misalnya anggukan kepala, senyuman, atau tepukan bahu.
5. Kompetisi dan Kooperasi
Persaingan merupakan insentif pada kondisi-kondisi tertentu, tetapi dapat merusak pada kondisi yang lain. Dalam kompetisi harus terdapat kesepakatan yang sama untuk menang. Kompetisi harus mengandung suatu tingkat kesamaan dalam sifat-sifat para peserta.
Ada tiga jenis persaingan yang efektif:
a. Kompetisi interpersonal antara teman-teman sebaya sering menimbulkan semangat persaingan.
b. Kompetisi kelompok di mana setiap anggota dapat memberikan sumbangan dan terlibat di dalam keberhasilan kelompok merupakan motivasi yang sangat kuat.
c. Kompetisi dengan diri sendiri, yaitu dengan catatan tentang prestasi terdahulu, dapat merupakan motivasi yang efektif.
Adapun kebutuhan akan realisasi diri, diterima oleh kelompok, dan kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan dapat lebih banyak dipenuhi dengan cara kerja sama. Menurut Lowry dan Rankin (1969), kerja sama adalah fungsi utama dan merupakan bentuk yang paling dasar dari hubungan-hubungan antar kelompok (dalam Hamalik, Umar, 2000:186).
6. Pemberian harapan
Harapan selalu mengacu ke depan. Artinya, jika seseorang berhasil melaksanakan tugasnya atau berhasil dalam kegitan belajarnya, dia dapat memperoleh dan mencapai harapan-harapan yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Itu sebabnya pemberian harapan kepada siswa dapat menggugah minat dan motivasi belajar asalkan siswa yakin bahwa harapannya bakal terpenuhi kelak. Harapan itu dapat merupakan hadiah, kedudukan, nama baik, atau sejenisnya. Sebaliknya, cara ini tidak menghasilkan apa-apa jika tidak memenuhi harapan yang pernah diberikan kepada para siswa.
F. Model Pembelajaran Tuntas
1. Pengertian
Belajar tuntas merupakan model pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam kelas, dengan asumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua peserta didik akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh bahan yang dipelajari (Ramayulis, 2005:193).
Berdasarkan uraian di atas, maka model belajar tuntas akan terlaksana apabila, (1) siswa menguasai semua bahan pelajaran yang disajikan secara penuh, (2) bahan pengajaran dibetulkan secara sistematis.
Dalam proses pembelajaran dimungkinkan bagi guru untuk menetapkan tingkat penguasaan yang diharapkan dari setiap peserta didik dengan menyediakan berbagai kemungkinan belajar dan meningkatan mutu pembelajaran. Guru harus mempu meyakinkan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai penguasaan penuh dalam belajar.
Menurut Carrol (dalam Ramayulis 2005:193) pada dasarnya bakat merupakan indeks kemampuan seseorang, melainkan sebagai ukuran kecepatan belajar (measures of learning rate). Artinya seorang yang memiliki bakat tinggi memerlukan waktu relatif sedikit untuk mencapai taraf penguasaan bahan dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki bakat rendah. Dengan demikian peserta didik dapat mencapai penguasaan penuh terhadap bahan yang disajikan, bila kualitas pembelajaran dan kesempatan waktu belajar dibuat tepat sesuai denagn kebutuhan masing-masing peserta didik.
Berdasarkan uraian di atas maka model belajar dilandasi oleh dua asumsi yaitu:
a. Bahwa adanya korelasi antara tingkat keberhasilan dengan kemampuan potensial (bakat). Hal ini dilandasi teori tentang bakat yang dikemukakan oleh Carrol yang menyatakan bahwa apabila para peserta didik didistibusikan secara normal dengan memperhatikan kemampuannya secara potensial untuk beberapa bidang pengajaran, kemudian mereka diberi pengajaran yang sama dan hasil belajarnya diukur, ternyata akan menunujukkan distribusi normal. Hal ini berarti bahwa peserta didik yang berbakat cenderung untuk memperoleh nilai tinggi (Ramayulis,194:1990).
b. Apabila dilaksanakan secara sistematis, maka semua peserta didik akan mampu menguasai bahan yang disajikan kepadanya.
2. Strategi Belajar Tuntas
Menurut Benyamin S. Bloom (Ramayulis,194:1990) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam belajar tuntas yaitu:
a. Menentukan unit pelajaran (dipecah untuk setiap satu dua minggu).
b. Merumuskan tujuan pengajaran (secara khusus dan terukur).
c. Menentukan standar ketuntasan (patokan berupa persentase).
d. Menyusun dianostik test, test formatif sebagai dasar umpan balik.
e. Mempersiapkan seperangkan tugas untuk dipelajari.
f. Mempersiapkan seperangkat pengajaran korektif (bagi peserta didik yang lemah).
g. Pelaksanaan pengajaran biasa (group based instruction).
h. Evaluasi sumatif, (apabila selesai satu unit).
Strategi belajar tuntas dikembangkan oleh Bloom di atas meliputi tiga bagian, yaitu:
a. Mengidentifikasi prakondisi
b. Mengembangkan prosedur operasional
c. Hasil belajar
Strategi tersebut diimplementasikan dalam sistem pembelajaran klasikal maupun individual dengan memberikan bumbu sesuai dengan taraf kemampuan individu peserta didik berupa corrective technique, semacam pengajaran remedial, yang dilakukan dengan memberikan pengajaran terhadap tujuan yang gagal dicapai peserta didik, dengan prosedur dan metode yang berbeda dengan sebelumnya. Memberikan tambahan waktu kepada tambahan waktu kepada peseta didik yang membutuhkan (belum menguasai bahan secara tuntas).
Strategi belajar tuntas dapat dibedakan dari pengajaran non belajar tuntas terutama dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Pelaksanaan test secara teratur untuk memperoleh balikan terhadap bahan yang diajarkan sebagai alat untuk mendiagnosa kemajuan (diagnostic progress test).
b. Peserta didik baru dapat melangkah pada pelajaran berikutnya setelah ia benar-benar menguasai bahan pelajaran sebelumnya sesuai dengan patokan yang ditetapkan.
c. Pelayanan bimbingan dan penyuluhan terhadap anak didik yang gagal mencapai taraf penguasaan penuh, melalui pengajaran korektif, yang merupakan pengajaran kembali, pengajaran tutorial, restrukturasi, kegiatan balajar dan pengajaran kembali kebiasaan-kebiasaan belajar peserta didik, sesuai dengan waktu yang diperlukan masing-masing.
H. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian pustaka tersebut di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, ”Dengan menerapkan model pembelajaran tuntas, prestasi belajar siswa akan meningkat, begitu juga motivasi belajar mereka".
BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai.
Menurut Sukidin dkk. (2002:54) ada 4 macam bentuk penelitian tindakan, yaitu: (1) penelitian tindakan guru sebagai peneliti, (2) penelitian tindakan kolaboratif, (3) penelitian tindakan simultan terintegratif, dan (4) penelitian tindakan sosial eksperimental.
Keempat bentuk penelitian tindakan di atas, ada persamaan dan perbedaannya. Menurut Oja dan Smulyan sebagaimana dikutip oleh Kasbolah, (2000) (dalam Sukidin, dkk. 2002:55), ciri-ciri dari setiap penelitian tergantung pada: (1) tujuan utamanya atau pada tekanannya, (2) tingkat kolaborasi antara pelaku peneliti dan peneliti dari luar, (3) proses yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan (4) hubungan antara proyek dengan sekolah.
Dalam penelitian ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, dimana guru sangat berperan sekali dalam proses penelitian tindakan kelas. Dalam bentuk ini, tujuan utama penelitian tindakan kelas ialah untuk meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, guru terlibat langsung secara penuh dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kehadiran pihak lain dalam penelitian ini peranannya tidak dominan dan sangat kecil.
Penelitian ini mengacu pada perbaikan pembelajaran yang berkesinambungan. Kemmis dan Taggart (1988:14) menyatakan bahwa model penelitian tindakan adalah berbentuk spiral. Tahapan penelitian tindakan pada suatu siklus meliputi perencanaan atau pelaksanaan observasi dan refleksi. Siklus ini berlanjut dan akan dihentikan jika sesuai dengan kebutuhan dan dirasa sudah cukup.
A. Rancangan Penelitian
Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi dimasyarakat atau sekolompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan (Arikunto, 2002:82). Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian tidakan adalah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan invovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Dalam prosesnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat saling mendukung satu sama lain.
Sedangkan tujuan penelitian tindakan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:
1. Permasalahan atau topik yang dipilih harus memenuhi kriteria, yaitu benar-benar nyata dan penting, menarik perhatian dan mampu ditangani serta dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan.
2. Kegiatan penelitian, baik intervensi maupun pengamatan yang dilakukan tidak boleh sampai mengganggu atau menghambat kegiatan utama.
3. Jenis intervensi yang dicobakan harus efektif dan efisien, artinya terpilih dengan tepat sasaran dan tidak memboroskan waktu, dana dan tenaga.
4. Metodologi yang digunakan harus jelas, rinci, dan terbuka, setiap langkah dari tindakan dirumuskan dengan tegas sehingga orang yang berminat terhadap penelitian tersebut dapat mengecek setiap hipotesis dan pembuktiannya.
5. Kegiatan penelitian diharapkan dapat merupakan proses kegiatan yang berkelanjutan (on-going), mengingat bahwa pengembangan dan perbaikan terhadap kualitas tindakan memang tidak dapat berhenti tetapi menjadi tantangan sepanjang waktu. (Arinkunto, 2002:82-83).
Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart (dalam Arikunto, 2002: 83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3.1 Alur PTK
Penjelasan alur di atas adalah:
1. Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran.
2. Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya model pembelajaran tuntas.
3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh pengamat.
4. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat membuat rangcangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya.
Observasi dibagi dalam tiga putaran, yaitu putaran 1, 2, dan 3, dimana masing putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir masing putaran. Dibuat dalam tiga putaran dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pengajaran yang telah dilaksanakan.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SDN ABC Kec. Kota Jakarta tahun pelajaran 2009/2010.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April semester genap 2009/2010.
C. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas IV SDN ABC Kec. Kota Jakarta tahun pelajaran 2009/2010 pada pokok bahasan kisah-kisah Nabi.
D. Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan melalui 5 tahap, yaitu, (1) tahap perencanaan, (2) tahap persiapan, dan (3) tahap pelaksanaan, (4) tahap pengolahan data, dan (5) penyusunan Laporan. Tahap-tahap tersebut dapat dirinci seperti sebagai berikut.
1. Tahap Perencanaan
Pada tahap perencanaan ini kegiatan yang dilakukan meliputi, (1) observasi di sekolah dan diskusi dengan mitra guru, (2) penyusunan proposal penelitian.
2. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan ini meliputi, (1) pembuatan RP (rencana pembelajaran), (2) pembuatan LO (lembar observsi), (3) pembuatan soal tes formatif, (4) pembuatan angket untuk mengamati motivasi belajar, (5) pembuatan rambu-rambu penilaian, (5) uji coba instrumen, dan (6) seleksi dan revisi instrumen.
3. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan yang banyak berhubungan dengan lapangan dan pengolahan hasil penelitian. Tahap pelaksanaan meliputi, (1) tahap pengumpulan data dan (2) tahap pengolahan data.
4. Tahap Penyelesaian
Pada tahap ini meliputi, (1) penyusunan laporan penelitian dan (2) penggandaan laporan.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen adalah alat pengumpul data seperti, tes, kuesioner, observasi, skala sikap, sosiometri, wawancara dan lain-lain.
Instrumen atau alat ukur dalam penelitian ini adalah berupa tes. Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan baik secara tertulis atau lisan atau secara perbuatan (Sudjana dan Ibrahim, 1996:100).
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Silabus
Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran pengelolahan kelas, serta penilaian hasil belajar.
2. Rencana Pelajaran (RP)
Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-masing RP berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar.
3. Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar
a. Lembar observasi pengelolaan model pembelajaran tuntas, untuk mengamati kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.
b. Lembar observasi aktivitas siswa dan guru, untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran.
4 Tes formatif
Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep Pendidikan Agama Islam transaksi keuangan. Tes formatif ini diberikan setiap akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan adalah pilihan ganda (objektif). Sebelumnya soal-soal ini berjumlah 46 soal yang telah diujicoba, kemudian penulis mengadakan analisis butir soal tes yang telah diuji validitas dan reliabilitas pada tiap soal. Analisis ini digunakan untuk memilih soal yang baik dan memenuhi syarat digunakan untuk mengambil data. Langkah-langkah analisis butir soal adalah sebagai berikut:
a. Validitas Tes
Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat. Validitas butir soal atau validitas item digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan masing-masing butir soal. Sehingga dapat ditentukan butir soal yang gagal dan yang diterima. Tingkat kevalidan ini dapat dihitung dengan korelasi Product Moment:
(Arikunto, 2002: 72)
Dengan: rxy : Koefisien korelasi product moment
N : Jumlah peserta tes
ΣY : Jumlah skor total
ΣX : Jumlah skor butir soal
ΣX2 : Jumlah kuadrat skor butir soal
ΣXY : Jumlah hasil kali skor butir soal
b. Reliabilitas
Suatu tes dikatanan reilabel apabila tes tersebut menunjukkan hasil-hasil yang mantap. Antara validitas dengan reliabelnya suatu soal berhubungan erat, yaitu untuk memenuhi syarat relaiabilitas, suatu soal harus valid dulu. Oleh karena itu reliabilitas suatu soal tidak perlu diragukan lagi apabila soal tersebut benar-benar sudah valid, jadi soal yang valid pasti reliabel. Reliabilitas butir soal dalam penelitian ini menggunakan rumus belah dua sebagai berikut:
(Arikunto, 2002:93)
Dengan: r11 : Koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan
r1/21/2 : Korelasi antara skor-skor setiap belahan tes
Kriteria reliabilitas tes jika harga r11 dari perhitungan lebih besar dari harga r pada tabel product moment maka tes tersebut reliabel.
c. Taraf Kesukaran
Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal adalah indeks kesukaran. Rumus yang digunakan untuk menentukan taraf kesukaran adalah:
(Arikunto, 2002:208)
Dengan: P : Indeks kesukaran
B : Banyak siswa yang menjawab soal dengan benar
Js : Jumlah seluruh siswa peserta tes
Kriteria untuk menentukan indeks kesukaran soal adalah sebagai berikut:
• Soal dengan P = 0,000 sampai 0,300 adalah sukar
• Soal dengan P = 0,301 sampai 0,700 adalah sedang
• Soal dengan P = 0,701 sampai 1,000 adalah mudah
d. Daya Pembeda
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks diskriminasi adalah sebagai berikut:
(Arikunto, 2002:211)
Dimana:
D : Indeks diskriminasi
BA : Banyak peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar
BB : Banyak peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar
JA : Jumlah peserta kelompok atas
JB : Jumlah peserta kelompok bawah
Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar.
Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar
Kriteria yang digunakan untuk menentukan daya pembeda butir soal sebagai berikut:
• Soal dengan D = 0,000 sampai 0,200 adalah jelek
• Soal dengan D = 0,201 sampai 0,400 adalah cukup
• Soal dengan D = 0,401 sampai 0,700 adalah baik
• Soal dengan D = 0,701 sampai 1,000 adalah sangat baik
5. Analisis Item Butir Soal
Sebelum melaksanakan pengambilan data melalui instrumen penelitian berupa tes dan mendapatkan tes yang baik, maka data tes tersebut diuji dan dianalisis. Uji coba dilakukan pada siswa di luar sasaran penelitian. Analisis tes yang dilakukan meliputi:
a. Validitas
Validitas butir soal dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan tes sehingga dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Dari perhitungan 46 soal diperoleh 10 soal tidak valid dan 30 soal valid. Hasil dari validitas soal-soal dirangkum dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.1. Soal Valid dan Tidak Valid Tes Formatif Siswa
Soal Valid Soal Tidak Valid
1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 5, 6, 8, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 40,
b. Reliabilitas
Soal-soal yang telah memenuhi syarat validitas diuji reliabilitasnya. Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien reliabilitas r11 sebesar 0, 423. Harga ini lebih besar dari harga r product moment. Untuk jumlah siswa (N = 45 dengan r (95%) = 0,294. Dengan demikian soal-soal tes yang digunakan telah memenuhi syarat reliabilitas. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
c. Taraf Kesukaran (P)
Taraf kesukaran digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal. Hasil analisis menunjukkan dari 46 soal yang diuji terdapat:
• 22 soal mudah
• 14 soal sedang
• 10 soal sukar
d. Daya Pembeda
Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah.
Dari hasil analisis daya pembeda diperoleh soal yang berkriteria jelek sebanyak 16 soal, berkriteria cukup 21 soal, berkriteria baik 9 soal. Uraian secara lengkap analisis daya pembeda soal tes dapat dilihat pada lampiran.
Dengan demikian soal-soal tes yang digunakan telah memenuhi syara-syarat validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda.
F. Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran.
Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.
Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu:
1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif
Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan:
Dengan : = Nilai rata-rata
Σ X = Jumlah semua nilai siswa
Σ N = Jumlah siswa
2. Untuk ketuntasan belajar
Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994 (Depdikbud, 1994), yaitu seorang siswa telah tuntas belajar bila telah mencapai skor 65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65%. Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut:
3. Untuk lembar observasi
a. Lembar observasi pengelolaan model pembelajaran tuntas.
Untuk menghitung lembar observasi pengelolaan model pembelajaran tuntas digunakan rumus sebagai berikut:
Dimana: P1 = pengamat 1 dan P2 = pengamat 2
b. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa
Untuk menghitung lembar observasi aktivitas guru dan siswa digunakan rumus sebagai berikut:
dengan
Dimana: % = Persentase pengamatan
= Rata-rata
= Jumlah rata-rata
P1 = Pengamat 1
P2 = Pengamat 2
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data penelitian yang diperoleh berupa data observasi berupa pengamatan pengelolaan model pembelajaran tuntas dan pengamatan aktivitas siswa dan guru pada akhir pembelajaran, dan data tes formatif siswa pada setiap siklus.
Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan pengelolaan model pembelajaran tuntas yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran tuntas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan data pengamatan aktivitas siswa dan guru.
Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkan proses belajar mengajar dengan menerapkan model pembelajaran tuntas.
A. Analisis Data Penelitian Persiklus
1. Siklus I
a. Tahap Perencanaan
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengolahan model pembelajaran tuntas, dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa.
b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 2 April 2009 di Kelas IV dengan jumlah siswa 45 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar, sedangkan yang bertindak sebagai pengamat adalah kepala sekolah dengan dibantu seorang guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar.
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1. Pengelolan Pembelajaran Pada Siklus I
No Aspek yang diamati Penilaian Rata-rata
P1 P2
I Pengamatan KBM
A. Pendahuluan
1. Memotivasi siswa
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran
B. Kegiatan Inti
1. Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan bersama siswa
2. Membimbing siswa melakukan kegiatan
3. Membimbing siswa mendiskusikan hasil kegiatan dalam kelompok
4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil penyelidikan
5. Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep
C. Penutup
1. Membimbing siswa membuat rangkuman
2. Memberikan evaluasi
I Pengelolaan Waktu 2 2 2
III Antusiasme Kelas
1. Siswa Antusias
2. Guru Antusias
Jumlah 32 32 32
Keterangan : Nilai : Kriteria
1 : Tidak Baik
2 : Kurang Baik
3 : Cukup Baik
4 : Sangat Baik
Berdasarkan tabel di atas aspek-aspek yang mendapatkan kriteria kurang baik adalah memotivasi siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, pengelolaan waktu, dan siswa antusias. Keempat aspek yang mendapat penilaian kurang baik di atas, merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada siklus I. Dan akan dijadikan bahan kajian untuk refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus II.
Hasil observasi berikutnya adalah aktivitas guru dan siswa seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.2. Aktivitas Guru Dan Siswa Pada Siklus I
No Aktivitas Guru yang diamati Persentase
Menyampaikan tujuan
Memotivasi siswa/merumuskan masalah
Mengkaitkan dengan pelajaran berikutnya
Menyampaikan materi/langkah-langkah/strategi
Menjelaskan materi yang sulit
Membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep
Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil kegiatan
Memberikan umpan balik
Membimbing siswa merangkum pelajaran 7,81
No Aktivitas Siswa yang diamati Persentase
Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru
Membaca buku siswa
Bekerja dengan sesama siswa
Diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru
Menyajikan hasil pembelajaran
Mengajukan/menanggapi pertanyaan/ide
Menulis yang relevan dengan KBM
Merangkum pembelajaran
Mengerjakan tes evaluasi
Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa aktivitas guru yang paling dominan pada siklus I adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep yaitu 20,31%. Aktivitas lain yang persentasenya cukup besar adalah memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dan menjelaskan materi yang sulit yaitu masing-masing sebesar 17,19% dan 12,50%. Sedangkan aktivitas siswa yang paling dominan adalah mengerjakan/memperhatikan penjelasan guru yaitu 21,09%. Aktivitas lain yang persentasenya cukup besar adalah bekerja dengan sesama siswa, diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru, dan membaca buku yaitu masing-masing 17,58% 13,48 dan 10,74%.
Pada siklus I, secara garis besar kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran tuntas sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun peran guru masih cukup dominan untuk memberikan penjelasan dan arahan karena model tersebut masih dirasakan baru oleh siswa.
Berikutnya adalah rekapitulasi hasil tes formatif siswa seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 4.3. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I
No Uraian Hasil Siklus I
Nilai rata-rata tes formatif
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Persentase ketuntasan belajar
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran tuntas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 68,22 dan ketuntasan belajar mencapai 66,67% atau ada 30 siswa dari 45 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya sebesar 66,67% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan model pembelajaran tuntas.
c. Refleksi
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut:
1) Guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa dan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran
2) Guru kurang maksimal dalam pengelolaan waktu
3) Siswa kurang aktif selama pembelajaran berlangsung
d. Refisi
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya.
1) Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan.
2) Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan
3) Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga siswa bisa lebih antusias.
2. Siklus II
a. Tahap perencanaan
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan model pembelajaran tuntas dan lembar observasi guru dan siswa.
b. Tahap kegiatan dan pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 di Kelas IV dengan jumlah siswa 45 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar, sedangkan yang bertindak sebagai pengamat adalah kepala sekolah dengan dibantu seorang guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4. Pengelolaan Pembelajaran Pada Siklus II
No Aspek yang diamati Penilaian Rata-rata
P1 P2
I Pengamatan KBM
A. Pendahuluan
1. Memotivasi siswa
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran
B. Kegiatan Inti
1. Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan bersama siswa
2. Membimbing siswa melakukan kegiatan
3. Membimbing siswa mendiskusikan hasil kegiatan dalam kelompok
4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil peneyelidikan
5. Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep
C. Penutup
1. Membimbing siswa membuat rangkuman
2. Memberikan evaluasi
II Pengelolaan Waktu 3 3 3
III Antusiasme Kelas
1. Siswa Antusias
2. Guru Antusias
Jumlah 41 43 42
Keterangan : Nilai : Kriteria
1 : Tidak Baik
2 : Kurang Baik
3 : Cukup Baik
4 : Sangat Baik
Dari tabel diatas, tampak aspek-aspek yang diamati pada kegiatan belajar mengajar (siklus II) yang dilaksanakan oleh guru dengan menerapkan model pembelajaran tuntas mendapatkan penilaian yang cukup baik dari pengamat. Maksudnya dari seluruh penilaian tidak terdapat nilai kurang. Namum demikian penilaian tersebut belum merupakan hasil yang optimal, untuk itu ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk penyempurnaan penerapan pembelajaran selanjutnya. Aspek-aspek tersebut adalah memotivasi siswa, membimbing siswa merumuskan kesimpulan/ menemukan konsep, dan pengelolaan waktu.
Dengan penyempurnaan aspek-aspek di atas dalam penerapan model pembelajaran tuntas diharapkan siswa dapat menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari dan mengemukakan pendapatnya sehingga mereka akan lebih memahami tentang apa yang telah mereka lakukan.
Berikut disajikan hasil observasi aktivitas guru dan siswa:
Tabel 4.5. Aktivitas Guru Dan Siswa Pada Siklus II
No Aktivitas Guru yang diamati Persentase
9 Menyampaikan tujuan
Memotivasi siswa/merumuskan masalah
Mengkaitkan dengan pelajaran berikutnya
Menyampaikan materi/langkah-langkah/strategi
Menjelaskan materi yang sulit
Membimbing dan mengamati siswa dalam menentukan konsep
Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil kegiatan
Memberikan umpan balik
Membimbing siswa merangkum pelajaran 71,81
No Aktivitas Siswa yang diamati Persentase
9 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru
Membaca buku siswa
Bekerja dengan sesama siswa
Diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru
Menyajikanhasil pembelajaran
Mengajukan/menanggapi pertanyaan/ide
Menulis yang relevan dengan KBM
Merangkum pembelajaran
Mengerjakan tes evaluasi/latihan 12,11
Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa aktivitas guru yang paling dominan pada siklus II adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep yaitu 23,44%. Jika dibandingkan dengan siklus I, aktivitas ini mengalami peningkatan. Selain itu aktivitas guru yang mengalami peningkatan adalah menjelaskan materi yang sulit sebesar 14,06%. Meminta siwa mendiskusikan dan menyajikan hasil kegiatan 10,93%. Disamping itu ada juga aktivitas guru yang mengalami penurunan antara lain memotivasi siswa dan mengaitkan dengan materi sebelumnya masing-masing menjadi 6,25%, memberi umpan balik menjadi 15,63% dan membimbing siswa merangkum pelajaran menjadi 6,25%
Sedangkan untuk aktivitas siswa yang paling dominan pada siklus II adalah bekerja dengan sesama siswa yaitu 19,53%. Jika dibandingkan dengan siklus I, aktivitas ini mengalami peningkatan. Aktivitas siswa yang mengalami peningkatan adalah membaca buku menjadi 13,67%, diskusi antar siswa/antar siswa dengan guru menjadi 14,06%, menyajikan hasil pembelajaran menjadi 7,42%, mengajukan pertanyaan/ide dan merangkum pemelajaran masing-masing menjadi 9,38%.
Aktivitas lainnya yang mengalami penurunan adalah menulis yang relevan dengan KBM menjadi 12,11% dan mengerjakan tes evaluasi menjadi 6.25%.
Berikutnya adalah rekapitulasi hasil tes formatif siswa terlihat pada tabel berikut.
Tabel 4.6. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II
No Uraian Hasil Siklus II
1
2
3 Nilai rata-rata tes formatif
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Persentase ketuntasan belajar 74,67
34
75,56
Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 74,67 dan ketuntasan belajar mencapai 75,56% atau ada 34 siswa dari 45 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan dinginkan guru dengan menerapkan model pembelajaran tuntas.
c. Refleksi
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut:
1) Memotivasi siswa
2) Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep
3) Pengelolaan waktu
d. Revisi Rancangan
Pelaksanaan kegiatan belajar pada siklus II ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Maka perlu adanya revisi untuk dilaksanakan pada siklus II antara lain:
1) Guru dalam memotivasi siswa hendaknya dapat membuat siswa lebih termotivasi selama proses belajar mengajar berlangsung.
2) Guru harus lebih dekat dengan siswa sehingga tidak ada perasaan takut dalam diri siswa baik untuk mengemukakan pendapat atau bertanya.
3) Guru harus lebih sabar dalam membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep.
4) Guru harus mendistribusikan waktu secara baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
5) Guru sebaiknya menambah lebih banyak contoh soal dan memberi soal-soal latihan pada siswa untuk dikerjakan pada setiap kegiatan belajar mengajar.
3. Siklus III
a. Tahap Perencanaan
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan model pembelajaran tuntas dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa.
b. Tahap kegiatan dan pengamatan
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada tanggal 16 April 2009 di Kelas IV dengan jumlah siswa 45 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar, sedangkan yang bertindak sebagai pengamat adalah kepala sekolah dengan dibantu seorang guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun data hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7. Pengelolaan Pembelajaran Pada Siklus III
No Aspek yang diamati Penilaian Rata-rata
P1 P2
I Pengamatan KBM
A. Pendahuluan
1. Memotivasi siswa
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran
B. Kegiatan Inti
1. Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan bersama siswa
2. Membimbing siswa melakukan kegiatan
3. Membimbing siswa mendiskusikan hasil kegiatan dalam kelompok
4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil peneyelidikan
5. Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep
C. Penutup
1. Membimbing siswa membuat rangkuman
2. Memberikan evaluasi
II Pengelolaan Waktu 3 3 3
III Antusiasme Kelas
1. Siswa Antusias
2. Guru Antusias
Jumlah 45 44 44,5
Keterangan : Nilai : Kriteria
1 : Tidak Baik
2 : Kurang Baik
3 : Cukup Baik
4 : Sangat Baik
Dari tabel di atas, dapat dilihat aspek-aspek yang diamati pada kegiatan belajar mengajar (siklus III) yang dilaksanakan oleh guru dengan menerapkan model pembelajaran tuntas mendapatkan penilaian cukup baik dari pengamat adalah memotivasi siswa, membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep, dan pengelolaan waktu.
Penyempurnaan aspek-aspek diatas dalam menerapkan model pembelajaran tuntas diharapkan dapat berhasil semaksimal mungkin.
Tabel 4.8. Aktivitas Guru dan Siswa Pada Siklus III
No Aktivitas Guru yang diamati Persentase
1
9 Menyampaikan tujuan
Memotivasi siswa/merumuskan masalah
Mengkaitkan dengan pelajaran berikutnya
Menyampaikan materi/langkah-langkah/strategi
Menjelaskan materi yang sulit
Membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep
Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil kegiatan
Memberikan umpan balik
Membimbing siswa merangkum pelajaran 7,81
No Aktivitas Siswa yang diamati Persentase
9 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru
Membaca buku siswa
Bekerja dengan sesama siswa
Diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru
Menyajikanhasil pembelajaran
Mengajukan/menanggapi pertanyaan/ide
Menulis yang relevan dengan KBM
Merangkum pembelajaran
Mengerjakan tes evaluasi/latihan 12,50
Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa aktivitas guru yang paling dominan pada siklus III adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep yaitu 20,31%, aspek ini menurun kembali seperti pada siklus I. Sedangkan aktivitas menjelaskan materi yang sulit, meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil pembelajaran, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab menurun masing-masing menjadi sebesar 10,94%, 6,25%, dan 7,81%
Aktivitas lain yang mengalami peningkatan adalah mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya dan menyampaikan langkah-langkah strategis masing menjadi 10,94% dan 17,19%. Adapun aktivitas yang lain tidak mengalami perubahan.
Sedangkan untuk aktivitas siswa yang paling dominan pada siklus III adalah membaca buku yaitu sebesar 19,53% dan diskusi antar siswa/antar siswa dengan guru menjadi sebesar 19,14%, aspek ini mengalami peningkatan dibanding siklus sebelumnya. aktivitas lain yang mengalami peningkatan adalah mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru menjadi 12,50%, dan mengerjakan tes evaluasi menjadi sebesar 6,844%.
Sedangkan aktivitas yang mengalami penurunan adalah bekerja sama dengan sesama siswa menjadi 13,87%, mengajukan pertanyaan/ide menjadi 5,86%, menulis yang relevan dengan KBM menjadi 7,03% dan merangkum pembelajaran menjadi 7,81%.
Berikutnya adalah rekapitulasai hasil tes formatif siswa seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 4.9. Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus III
No Uraian Hasil Siklus III
1
2
3 Nilai rata-rata tes formatif
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Persentase ketuntasan belajar 79,78
39
86,67
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 78,60 dan dari 45 siswa yang telah tuntas sebanyak 39 siswa dan 6 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 86,67% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran tuntas sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan.
c. Refleksi
Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan menerapan model pembelajaran tuntas. Dari data-data yang telah diperoleh dapat duraikan sebagai berikut:
1) Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar.
2) Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar berlangsung.
3) Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik.
4) Hasil belajar siswsa pada siklus III mencapai ketuntasan.
d. Revisi Pelaksanaan
Pada siklus III guru telah menerapkan model pembelajaran tuntas dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan model pembelajaran tuntas dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
B. Pembahasan
1. Ketuntasan Hasil belajar Siswa
Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran tuntas memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 66,67%, 75,56%, dan 86,67%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai.
2. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran
Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan model pembelajaran tuntas dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan.
3. Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran
Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada pada pokok bahasan kisah-kisah Nabi dengan model pembelajaran tuntas yang paling dominan adalah bekerja dengan sesama siswa, mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif.
Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan model pembelajaran tuntas dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan dari tujuan penelitian tindakan kelas (action research) untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang terjadi di kelas, serta berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan selama tiga siklus, hasil seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Model pembelajaran tuntas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam, hal ini terlihat dengan ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (66,67%), siklus II (75,56%), siklus III (86,67%).
2. Model pembelajaran tuntas dapat menjadikan siswa merasa dirinya mendapat perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide dan pertanyaan, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok dan mampu mempertangungjawabkan segala tugas individu maupun kelompok, serta penerapan model pembelajaran tuntas mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
B. Saran
Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut:
1. Untuk melaksanakan model pembelajaran tuntas memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan model pembelajaran tuntas dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal.
2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di SDN ABC Kec. Kota Jakarta tahun pelajaran 2009/2010.
4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:Rineksa Cipta.
Combs. Arthur. W. 1984. The Profesional Education of Teachers. Allin and Bacon, Inc. Boston.
Dahar, R.W. 1989. Teori-teori Belajar. Jakarta: Erlangga.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, Jakarta. Balai Pustaka.
Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineksa Cipta.
Djamarah. Syaiful Bahri. 2000. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineksa Cipta.
Hamalik, Oemar. 1994. Metode Pendidikan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hamalik,Oemar. 2000. Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Kemmis, S. dan Mc. Taggart, R. 1988. The Action Research Planner. Victoria Dearcin University Press.
Margono. 1997. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineksa Cipta.
Ngalim, Purwanto M. 1990. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nur, Moh. 2001. Pemotivasian Siswa untuk Belajar. Surabaya. University Press. Universitas Negeri Surabaya.
Poerwodarminto. 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Bina Ilmu.
Purwanto, N. 1988. Prinsip-prinsip dan Teknis Evaluasi Pengajaran. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Rustiyah, N.K. 1991. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Bina Aksara.
Sardiman, A.M. 1996. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Bina Aksara.
Sukidin, dkk. 2002. Manajemen Penelitian Tindakan Kelas. Surabaya: Insan Cendekia.
Suryosubroto, B. 1997. Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Jakarta: Rineksa Cipta.
Syah, Muhibbin. 1995. Psikologi Pendidikan, Suatu Pendekatan Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Lampiran 1
LEMBAR PENGAMATAN PENGELOLAAN KBM
Nama Sekolah : ………………. Nama Guru : ………………………
Mata Pelajaran : ………………. Hari/tanggal : ………………………
Sub Konsep : ………………. Pukul : ………………………
Petunjuk
Berikan penilan anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai.
No Aspek yang diamati Penilaian
1 2 3 4
I Pelaksanaan
A. Pendahuluan
1. Memotivasi Siswa
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran
B. Kegiatan Inti
1. Mendiskusikan langkah kegiatan bersama siswa.
2. Membimbing siswa melakukan kegiatan.
3. Membimbing siswa mendiskusikan hasil kegiatan dalam kelompok
4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil penyelidikan.
5. Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep.
C. Penutup
1. Membimbing siswa membuat rangkuman.
2. Memberikan evaluasi.
II Pengelolaan waktu
III Antusiasme kelas
1. Siswa antusias
2. Guru Antusias.
Keterangan Jakarta, ……….2009
1. Kurang baik Pengamat
2. Cukup baik
3. Baik
4. Sangat baik
(…………………………..)
Lampiran 2
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU DAN SISWA DALAM KBM
Nama Sekolah : Tanggal :
Kelas/semester : Waktu :
Bahan Kajian : Nama Guru :
Petunjuk Pengisian
Amatilah aktivitas gurudan siswa dalam kelompok sampel selama kegiatan belajar berlangsung kemudian isilah lembar observasi dengan prosedur sebagai berikut:
1. Pengamat dalam melakukan pengamatan duduk di tempat yang memungkinkan dapat melihat semua aktivitas siswa yang diamati.
2. Setiap 2 menit pengamat melakukan pengamatan aktivitas guru dan siswa yang dominan, kemudian ½ menit pengamat menuliskan kode kategori pengamatan.
3. Pengamatan ditujukan untuk kedua kelompok yang melakukan secara bergantian setiap periode waktu tiga menit.
4. Kode-kode kategori dituliskan secara berurutan sesuai dengan kejadian pada baris dan kolom yang tersedia.
5. Pengamatan dilakukan sejak guru memulai pelajaran dan dilakukan secara serempak.
Aktivitas guru Aktivitas siswa
1. Menyampaikan tujuan
2. Memotivasi siswa/merumusan masalah.
3. Mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan langkah-langkah/strategi
5. Menjelaskan materi yang sulit
6. Memebimbing menemukan konsep.
7. Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil kegiatan.
8. Memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab.
9. Membimbing siswa merangkum pelajaran. 1. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru.
2. Membaca buku.
3. Bekerja dengan sesama siswa
4. Diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru.
5. Menyajikan hasil pembelajaran
6. Mengajukan/menanggapi pertanyaan/ide.
7. Menulis yang relevan dengan KBM.
8. Merangkum pembelajaran.
9. Mengerjakan tes evaluasi.
Nama Guru:
Nama Murid: Nama Murid:
Nama Murid: Nama Murid:
Nama Murid: Nama Murid:
Nama Murid: Nama Murid:
Jakarta, 2009
Pengamat
(…………………….)
Lampiran 3
Data Pengamatan Pengelolaan KBM Pada Siklus I
No. Aspek yang diamati Penilaian
P1 P2
1 2 3 4 1 2 3 4
I Pelaksanaan
A. Pendahuluan
1. Memotivasi Siswa
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran
B. Kegiatan Inti
1. Mendiskusikan langkah kegiatan bersama siswa.
2. Membimbing siswa melakukan kegiatan.
3. Membimbing siswa mendiskusikan hasil kegiatan dalam kelompok
4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil penyelidikan
5. Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep.
C. Penutup
1. Membimbing siswa membuat rangkuman.
2. Memberikan evaluasi.
II Pengelolaan waktu √ √
III Antusiasme kelas
1. Siswa antusias
2. Guru Antusias.
Keterangan:
Dimana: P1 = pengamat 1
P2 = pengamat 2
Lampiran 4
Data Pengamatan Pengelolaan KBM Pada Siklus II
No. Aspek yang diamati Penilaian
P1 P2
1 2 3 4 1 2 3 4
I Pelaksanaan
A. Pendahuluan
1. Memotivasi Siswa
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran
B. Kegiatan Inti
1. Mendiskusikan langkah kegiatan bersama siswa.
2. Membimbing siswa melakukan kegiatan.
3. Membimbing siswa mendiskusikan hasil kegiatan dalam kelompok
4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil penyeledikan
5. Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep.
C. Penutup
1. Membimbing siswa membuat rangkuman.
2. Memberikan evaluasi.
√
√
II Pengelolaan waktu √ √
III Antusiasme kelas
1. Siswa antusias
2. Guru Antusias
Keterangan:
Dimana: P1 = pengamat 1
P2 = pengamat 2
Lampiran 5
Data Pengamatan Pengelolaan KBM Pada Siklus III
No. Aspek yang diamati Penilaian
P1 P2
1 2 3 4 1 2 3 4
I Pelaksanaan
A. Pendahuluan
1. Memotivasi Siswa
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran
B. Kegiatan Inti
1. Mendiskusikan langkah kegiatan bersama siswa.
2. Membimbing siswa melakukan kegiatan.
3. Membimbing siswa mendiskusikan hasil kegiatan dalam kelompok
4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil penyelidikan
5. Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep.
C. Penutup
1. Membimbing siswa membuat rangkuman.
2. Memberikan evaluasi.
√
√
II Pengelolaan waktu √ √
III Antusiasme kelas
3. Siswa antusias
4. Guru Antusias.
√
√
√
√
Keterangan:
Dimana: P1 = pengamat 1
P2 = pengamat 2
Lampiran 6
Data Pengamatan Aktivitas Guru dan Siswa Putaran I
No. Nama (Guru-Siswa) P RP I (80 menit) Jumlah
Nama Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P1 2 3 3 3 4 6 3 5 3 32
P2 3 2 2 3 4 7 3 6 2 32
Rata-rata X 2.5 2.5 2.5 3 4 6.5 3 5.5 2.5 32
Prosentase % 7.81 7.81 7.81 9.38 12.50 20.31 9.38 17.19 7.81 100
1 Nama Siswa P1 4 4 6 4 2 3 3 2 4 32
P2 8 2 5 5 2 2 4 2 2 32
2 Nama Siswa P1 6 4 6 4 2 3 2 2 3 32
P2 8 2 7 5 1 2 3 2 2 32
3 Nama Siswa P1 5 3 7 5 1 3 2 2 4 32
P2 10 4 4 4 1 2 3 2 2 32
4 Nama Siswa P1 4 4 7 5 2 3 2 3 2 32
P2 10 4 4 3 1 2 4 2 2 32
5 Nama Siswa P1 6 2 8 4 3 1 2 2 4 32
P2 8 3 4 5 3 3 2 2 2 32
6 Nama Siswa P1 6 4 6 4 1 3 2 2 4 32
P2 8 4 3 5 1 3 4 2 2 32
7 Nama Siswa P1 5 4 6 3 3 4 2 2 3 32
P2 5 4 4 5 3 3 3 3 2 32
8 Nama Siswa P1 6 3 8 4 3 1 2 2 3 32
P2 9 4 5 4 1 2 3 2 2 32
Jumlah P1 42
28
54
33
17
21
17
17
27
256
P2 66
27
36
36
13
19
26
17
16
256
Rata-rata X 54 27.5 45 34.5 15 20 21.5 17 21.5 256
Prosentase rata-rata % 21.09 10.74 17.58 13.48 5.86 7.81 8.40 6.64 8.40 100
Keterangan:
Rata-rata (x)
Prosentase rata-rata (%)
Lampiran 7
Data Pengamatan Aktivitas Guru dan Siswa Putaran II
No. Nama (Guru-Siswa) P RP I (90 menit) Jumlah
Nama Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P1 2 2 2 3 5 7 4 5 2 32
P2 3 2 2 3 4 8 3 5 2 32
Rata-rata X 2.5 2 2 3 4.5 7.5 3.5 5 2 32
Prosentase % 7.81 6.25 6.25 9.38 14.06 23.44 10.93 15.63 6.25 100
1 Nama Siswa P1 2 5 6 5 2 5 2 3 2 32
P2 3 5 6 5 2 4 2 3 2 32
2 Nama Siswa P1 3 4 7 5 2 4 2 3 2 32
P2 2 6 5 5 3 3 3 3 2 32
3 Nama Siswa P1 4 4 6 5 3 3 2 3 2 32
P2 4 4 7 4 2 3 3 3 2 32
4 Nama Siswa P1 4 6 6 4 1 5 2 2 2 32
P2 3 5 6 4 3 4 3 2 2 32
5 Nama Siswa P1 5 4 6 4 3 3 2 3 2 32
P2 5 5 5 4 4 1 4 2 2 32
6 Nama Siswa P1 5 2 7 6 1 2 3 4 2 32
P2 3 4 7 6 1 2 3 4 2 32
7 Nama Siswa P1 6 4 6 2 3 3 2 4 2 32
P2 4 3 9 4 2 1 4 3 2 32
8 Nama Siswa P1 4 3 6 5 3 3 3 3 2 32
P2 5 6 5 4 3 2 2 3 2 32
Jumlah P1 33
32
50
36
18
28
18
25
16
256
P2 29
38
50
36
20
20
24
23
16
256
Rata-rata X 31 35 50 36 19 24 21 24 16 256
Prosentase rata-rata % 12.11 13.67 19.53 14.06 7.42 9.38 8.20 9.38 6.25 100
Keterangan:
Rata-rata (x)
Prosentase rata-rata (%)
Lampiran 8
Data Pengamatan Aktivitas Guru dan Siswa Putaran III
No. Nama (Guru-Siswa) P RP I (90 menit) Jumlah
Nama Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P1 3 2 4 5 2 7 2 5 2 32
P2 3 2 3 6 5 6 2 4 2 33
Rata-rata X 2.5 2 3.5 5.5 3.5 6.5 2 4.5 2 32
Prosentase % 7.81 6.25 10.94 17.19 10.94 20.31 6.25 14.06 6.25 100
1 Nama Siswa P1 2 5 5 7 2 3 3 3 2 32
P2 3 6 5 6 3 2 2 3 2 32
2 Nama Siswa P1 5 6 4 6 2 3 2 2 2 32
P2 5 6 7 4 2 2 1 2 3 32
3 Nama Siswa P1 4 5 2 2 9 1 4 3 2 32
P2 3 5 6 6 1 2 4 2 3 32
4 Nama Siswa P1 4 6 5 6 2 2 3 2 2 32
P2 5 8 6 4 1 1 3 2 2 32
5 Nama Siswa P1 4 7 4 7 2 2 1 3 2 32
P2 5 9 4 7 0 1 2 2 2 32
6 Nama Siswa P1 4 6 4 8 2 2 2 2 2 32
P2 3 8 4 7 3 1 1 3 2 32
7 Nama Siswa P1 5 4 3 7 2 3 3 3 2 32
P2 3 7 6 6 3 1 1 2 3 32
8 Nama Siswa P1 5 5 2 7 2 2 3 4 2 32
P2 4 7 4 8 2 2 1 2 2 32
Jumlah P1 33
44
29
50
23
18
21
22
16
256
P2 31
56
42
48
15
12
15
18
19
256
Rata-rata X 32 50 35.5 49 19 15 18 20 17.5 256
Prosentase rata-rata % 12.50 19.53 13.87 19.14 7.42 5.86 7.03 7.81 6.84 100
Keterangan:
Rata-rata (x)
Prosentase rata-rata (%)
Lampiran 9
Hasil Tes Ulangan Harian Pada Siklus I
No. Nama Nilai Keterangan
T TT
1 Nama Siswa 100 √
2 Nama Siswa 60 √
3 Nama Siswa 80 √
4 Nama Siswa 60 √
5 Nama Siswa 70 √
6 Nama Siswa 80 √
7 Nama Siswa 70 √
8 Nama Siswa 50 √
9 Nama Siswa 70 √
10 Nama Siswa 40 √
11 Nama Siswa 90 √
12 Nama Siswa 60 √
13 Nama Siswa 70 √
14 Nama Siswa 70 √
15 Nama Siswa 70 √
16 Nama Siswa 50 √
17 Nama Siswa 90 √
18 Nama Siswa 50 √
19 Nama Siswa 70 √
20 Nama Siswa 70 √
21 Nama Siswa 40 √
22 Nama Siswa 80 √
23 Nama Siswa 70 √
24 Nama Siswa 80 √
25 Nama Siswa 50 √
26 Nama Siswa 70 √
27 Nama Siswa 70 √
28 Nama Siswa 80 √
29 Nama Siswa 70 √
30 Nama Siswa 50 √
31 Nama Siswa 60 √
32 Nama Siswa 100 √
33 Nama Siswa 70 √
34 Nama Siswa 70 √
35 Nama Siswa 80 √
36 Nama Siswa 60 √
37 Nama Siswa 50 √
38 Nama Siswa 80 √
39 Nama Siswa 70 √
40 Nama Siswa 70 √
41 Nama Siswa 70 √
42 Nama Siswa 60 √
43 Nama Siswa 80 √
44 Nama Siswa 70 √
45 Nama Siswa 50 √
Jumlah 3070
30 15
Keterangan:
T : Tuntas
TT : Tidak tuntas
Jumlah Siswa yang tuntas : 30
Jumlah siswa yang tidak tuntas : 15
Skor Maksimal Ideal : 4500
Skor Tercapai : 3070
Rata-rata Skor Tercapai : 68,22
Prosentase Ketuntasan : 66,67%
Lampiran 10
Hasil Tes Ulangan Harian Pada Siklus II
No. Nama Nilai Keterangan
T TT
1 Nama Siswa 100 √
2 Nama Siswa 60 √
3 Nama Siswa 90 √
4 Nama Siswa 70 √
5 Nama Siswa 70 √
6 Nama Siswa 90 √
7 Nama Siswa 70 √
8 Nama Siswa 50 √
9 Nama Siswa 80 √
10 Nama Siswa 50 √
11 Nama Siswa 100 √
12 Nama Siswa 60 √
13 Nama Siswa 80 √
14 Nama Siswa 70 √
15 Nama Siswa 80 √
16 Nama Siswa 60 √
17 Nama Siswa 90 √
18 Nama Siswa 60 √
19 Nama Siswa 70 √
20 Nama Siswa 70 √
21 Nama Siswa 50 √
22 Nama Siswa 80 √
23 Nama Siswa 80 √
24 Nama Siswa 90 √
25 Nama Siswa 60 √
26 Nama Siswa 80 √
27 Nama Siswa 80 √
28 Nama Siswa 90 √
29 Nama Siswa 80 √
30 Nama Siswa 60 √
31 Nama Siswa 70 √
32 Nama Siswa 100 √
33 Nama Siswa 80 √
34 Nama Siswa 80 √
35 Nama Siswa 80 √
36 Nama Siswa 70 √
37 Nama Siswa 50 √
38 Nama Siswa 80 √
39 Nama Siswa 90 √
40 Nama Siswa 80 √
41 Nama Siswa 70 √
42 Nama Siswa 70 √
43 Nama Siswa 80 √
44 Nama Siswa 80 √
45 Nama Siswa 60 √
Jumlah 3360
34 11
Keterangan:
T : Tuntas
TT : Tidak tuntas
Jumlah Siswa yang tuntas : 34
Jumlah siswa yang tidak tuntas : 11
Skor Maksimal Ideal : 4500
Skor Tercapai : 3360
Rata-rata Skor Tercapai : 74,67
Prosentase Ketuntasan : 75,56%
Lampiran 11
Hasil Tes Ulangan Harian Pada Siklus III
No. Nama Nilai Keterangan
T TT
1 Nama Siswa 100 √
2 Nama Siswa 70 √
3 Nama Siswa 90 √
4 Nama Siswa 80 √
5 Nama Siswa 80 √
6 Nama Siswa 90 √
7 Nama Siswa 90 √
8 Nama Siswa 60 √
9 Nama Siswa 90 √
10 Nama Siswa 60 √
11 Nama Siswa 100 √
12 Nama Siswa 70 √
13 Nama Siswa 80 √
14 Nama Siswa 80 √
15 Nama Siswa 80 √
16 Nama Siswa 70 √
17 Nama Siswa 90 √
18 Nama Siswa 60 √
19 Nama Siswa 80 √
20 Nama Siswa 80 √
21 Nama Siswa 60 √
22 Nama Siswa 90 √
23 Nama Siswa 80 √
24 Nama Siswa 90 √
25 Nama Siswa 70 √
26 Nama Siswa 90 √
27 Nama Siswa 90 √
28 Nama Siswa 90 √
29 Nama Siswa 80 √
30 Nama Siswa 60 √
31 Nama Siswa 80 √
32 Nama Siswa 100 √
33 Nama Siswa 80 √
34 Nama Siswa 80 √
35 Nama Siswa 80 √
36 Nama Siswa 70 √
37 Nama Siswa 50 √
38 Nama Siswa 90 √
39 Nama Siswa 80 √
40 Nama Siswa 80 √
41 Nama Siswa 90 √
42 Nama Siswa 80 √
43 Nama Siswa 80 √
44 Nama Siswa 80 √
45 Nama Siswa 70 √
Jumlah 3590
39 6
Keterangan:
T : Tuntas
TT : Tidak tuntas
Jumlah Siswa yang tuntas : 39
Jumlah siswa yang tidak tuntas : 6
Skor Maksimal Ideal : 4500
Skor Tercapai : 3590
Rata-rata Skor Tercapai : 79,78
Prosentase Ketuntasan : 86,67%
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MENERAPKAN MODEL PENGAJARAN TUNTAS PADA SISWA KELAS IV
SDN ABC KEC. KOTA JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
KARYA TULIS ILMIAH
Oleh
NAMA GURU S.Ag
NIP: 130 000 000
DINAS PENDIDIKAN
SDN ABC KEC. KOTA JAKARTA
2009
ABSTRAK
Nama Guru, 2008. Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Dengan Menerapkan Model Pengajaran Tuntas Pada Siswa Kelas IV SDN ABC Kec. Kota Jakarta Tahun Pelajaran 2009/2010
Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, model pembelajaran tuntas
Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah asal pakai, tetapi setelah melalui seleksi yang berkesesuaian dengan perumusan tujuan intruksional khusus. Sebab dalam kegiaatan belajar mengajar, mengajar bukan semata persoalan menceritakan. Belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari perenungan informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang langgeng. Yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar aktif.
Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: (a) Apakah penerapan model pembelajaran tuntas dapat meningkatkan prestasi siswa terhadap materi pelajaran Pendidikan Agama Islam (b) Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran tuntas dalam meningkatkan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam?
Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam, khususnya di SDN ABC Kec. Kota Jakarta, salah satunya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran tuntas. Dengan menerapkan metode pembelajaran ini diharapkan prestasi serta motivasi belajar Pendidikan Agama Islam dapat meningkat.
Tujuan penelitian tindakan ini adalah: (a) Ingin mengetahui bagaimanakah peningkatan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam setelah diterapkannya model pembelajaran tuntas. (b) Ingin mengetahui pengaruh model pembelajaran tuntas dalam meningkatkan prestasi dan motivasi belajar terhadap materi pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas IV SDN ABC Kec. Kota Jakarta tahun pelajaran 2009/2010. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar.
Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (66,67%), siklus II (75,56%), siklus III (86,67%).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran tuntas dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Siswa SDN ABC Kec. Kota Jakarta tahun pelajaran 2009/2010, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Abstrak iv
Daftar Isi vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Pemecahan Masalah 5
D. Batasan Masalah 5
E. Tujuan Penelitian 5
F. Manfaat Penelitian 6
G. Definisi Operasional 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar 8
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 10
C. Motivasi Belajar 11
D. Prinsip Motivasi 11
E. Teknik Mimotivasi Berdasarkan Kebutuhan 15
F. Model Pembelajaran Tuntas 18
G. Hipotesis Tindakan 21
BAB III METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian 24
B. Tempat dan Waktu Penelitian 27
C. Subyek Penelitian 28
D. Prosedur Penelitian 28
E. Instrumen Penelitian 29
F. Teknik Analisis Data 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Data Penelitian Persiklus 38
B. Pembahasan 55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 57
B. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 59


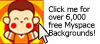










 21.40
21.40
 perpuskumayak
perpuskumayak
